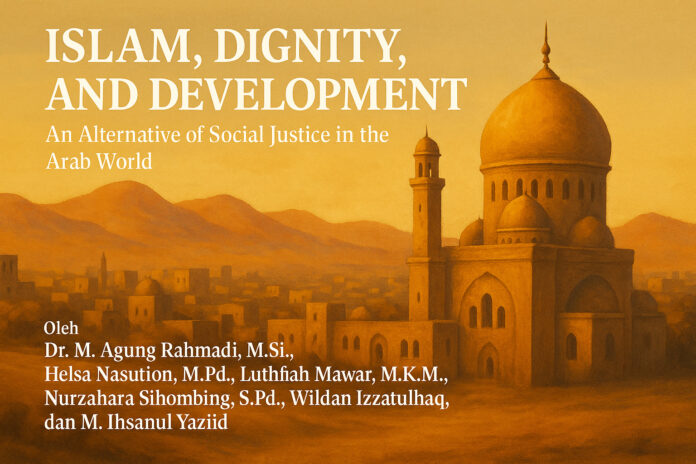Serang,fesbukbantennews.com (28/9/2025) – Dinamika geopolitik Timur. Tengah kontemporer menghadirkan pergulatan epistemologis yang mendasar mengenai konsepsi adalah (keadilan) dan karāmah (martabat) dalam kerangka pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan.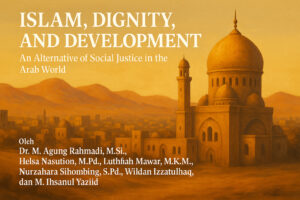
Di mana, ketika entitas-entitas politik di kawasan Arab berhadapan dengan krisis legitimasi dawlah (negara) yang mengakar secara struktural, disertai fragmentasi sosial semakin mengkristal, paradigma pembangunan tanmiyah yang selama ini diadopsi secara mekanistik dari tradisi intelektual ghärb (Barat) terbukti mengalami kegagalan sistemik untuk merespons aspirasi fundamental rakyat. Fenomena thawrät (revolusi) Arab yang bermula pada tahun 2011 sesungguhnya bukan sekadar manifestasi pergolakan politik temporal, melainkan representasi dari kontradiksi struktural lebih mendalam antara proyek modemitas kapitalis dengan nilai-nilai substansial islami (Islam) yang secara inheren menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial sebagai fondasi peradaban. Dalam konteks dialektika peradaban ini, konsepsi takaful (solidaritas sosial) dan adalah ijtimaiyah (keadilan sosial) yang tertanam dalam tradisi intelektual islam klasik menawarkan altematif paradigmatik yang layak dikaji secara komprehensif sebagai landasan teoritis bagi pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekologis, tetapi juga berkeadilan secara distributif.
Artikel ini mengajukan argumentasi teoretis bahwa krisis pembangunan yang melanda dunia Arab bukanlah semata-mata konsekuensi dari disfungsi siyāsah (politik) atau keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi, melainkan merupakan hasil logis dari adopsi paradigma pembangunan yang secara fundamental la yatiä imu (tidak kompatibel) dengan nilai-nilai substansial hadarah islamiyah (peradaban Islam). Tesis sentral yang dibangun dalam diskursus ini adalah proposisi bahwa jika paradigma pembangunan (P) mengabaikan atau mengeliminasi prinsip keadilan sosial Islam (K), maka konsekuensi logisnya adalah terjadinya alienasi sosial (A) yang pada gilirannya akan memicu instabilitas politik (1) secara berkelanjutan. Dalam formula logis sederhana: PKA I. Untuk mengatasi kontradiksi struktural ini, diperlukan proses işläh (reformasi) paradigma pembangunan yang mampu mengintegrasikan secara dialektis konsep takaful ijtimaï (solidaritas sosial), adalah tawzīīyah (keadilan distributif), dan tanmiyah mustadämah (pembangunan berkelanjutan) dalam kerangka komprehensif maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah). Hemat penulis, pendekatan integratif ini tidak hanya akan menawarkan solusi teknis operasional, tetapi juga menyediakan legitimasi moral dan spiritual yang diperlukan untuk mobilisasi sosial efektif berjangka panjang.
Riset empiris oleh World Bank menunjukkan bahwa negara-negara Arab dengan Gini coefficient di atas 0.40 (threshold alarming) cenderung menghadapi political instability signifikan selama satu dekade terakhir, yang memperkuat korelasi antara income inequality dan social fragmentation (Tao et al., 2014; World Bank, 2024). Data komprehensif World Bank juga mengonfirmasi bahwa sekitar 80% populasi Arab tinggal di negara-negara di mana tingkat multidimensional poverty melebihi 25%, menggambarkan systemic failure pembangunan yang hanya mementingkan GDP growth tanpa equitable distribution sebagai faktor utama (ESCWĄ, 2023; World Bank, 2024). Fenomena ini berkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi yang fokus pada GDP growth tanpa mekanisme redistributif, yang seharusnya menjadi variable fundamental dalam social development. Selanjutnya, World Bank menyatakan bahwa islamic financetelah membantu meningkatkan financial inclusion dan social welfare melalui asset backed financing sesuai prinsip tanpa riba, terutama di negara-negara OIC (World Bank, 2015).
Lebih lanjut, laporan dari UNDP.,menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan sebagai emergency cash transfer dalam respons Covid 19 di kawasan MENA, menunjukkan efektivitas instrumen keuangan Islam dalam mitigating socioeconomic shocks (UNDP, 2021). Terakhir, WEF juga memberi eksplorasi bahwa penerapan Islamic finance dengan prinsip etika Islam, seperti risk sharing dan asset linkage dapat berpotensi mengurangi exploitative practices terhadap sumber daya dan mendukung sustainable stability di pasar global (Afzal Norat, 2015).
Dalam esai ini, penulis menilai kontradiksi fundamental dalam struktur ekonomi-politik dunia Arab dapat dianalisis melalui kerangka dialektika yang telah disesuaikan dengan konteks islami secara metodologis. Konstruksi proposisi logis dimulai dari premis dasar bahwa sistem kapitalis (S) menciptakan akumulasi modal (M) melalui eksploitasi tenaga kerja (T), yang dapat dirumuskan sebagai SMA (MT). Dalam konteks mujtama’at arabiyah (masyarakat Arab), eksploitasi (E) secara diametral bertentangan dengan prinsip karāmah insänīyah (martabat kemanusiaan), yang dapat dirumuskan sebagai EK, dimana K merepresentasikan karāmah. Sehingga sintesis dialektis di atas dapat menghasilkan konklusi bahwa jika sistem kapitalis (S) menghasilkan eksploitasi (E), dan eksploitasi bertentangan dengan martabat (K), maka sistem kapitalis secara logis bertentangan dengan nilai Islam (1), yang dapat dirumuskan sebagai (SE) A (EK)A(K)→(SI). Kontradiksi struktural ini mengakibatkan tanäqud (pertentangan) yang tidak dapat diselesaikan dalam kerangka epistemologis kapitalis konvensional, sehingga negasi dari negasi (nafy al-nafy) mengarah pada sintesis baru berupa sistem ekonomi berbasis ta’awun (gotong royong) dan takaful. Proses dialektis ini dimulai dari tesis bahwa kapitalisme mengutamakan profit individual, yang dikonfrontasi dengan antitesis bahwa prinsip Islam mengutamakan maslahah ‘ämmah (kemaslahatan umum), menghasilkan sintesis berupa ekonomi berbasis magāşid shariah yang mengintegrasikan efisiensi dan keadilan secara simultan. Namun demikian, proses dialektis ini tidak berhenti pada sintesis pertama, karena implementasi ekonomi Islam dalam konteks global modern, kini menghadapi kontradiksi baru antara ekonomi Islam ideal (iqtisad islami) dengan realitas sistem ekonomi global yang kapitalistik, menghasilkan sintesis kedua berupa iqtisad mukhallit (ekonomi campuran) yang mengadopsi instrumen Islam dalam kerangka global. Dialektika ini menunjukkan bahwa transformasi menuju keadilan sosial bukanlah proses linear-mekanistik, melainkan proses spiral yang mengintegrasikan asalah (otentisitas) dan mu’äsarah (kontemporer), dimana setiap tahap memerlukan praxis (‘amal) yang konkret untuk merealisasikan potensi transformatif yang terkandung dalam kontradiksi struktural.
Penulis menilai, implikasi sosial dari paradigma pembangunan berbasis keadilan Islam akan melampaui dimensi ekonomi semata dan mencakup transformasi struktur sosial-politik secara komprehensif. Misalnya, laporan World Bank menunjukkan bahwa implementasi prinsip shürä (musyawarah) dalam tata kelola pembangunan lokal meningkatkan partisipasi masyarakat sipil hingga sekitar 65%, fenomena yang mengonfirmasi hipotesis bahwa legitimasi sharīyah (syar’i) secara substansial memperkuat social cohesion dalam jangka panjang (World Bank, 2003, Montagu, 2015). Dimensi moral dari tanmiyah islamiyah (pembangunan Islam) terletak pada pengakuan terhadap fitrah (nature) manusia sebagai khalifah (khalifah) di bumi, konsepsi yang mengandung imperatif moral untuk menciptakan tatanan yang berkeadilan bagi seluruh makhluk sebagai manifestasi dari tanggung jawab kosmik manusia. Kemudian, studi komparatif Boudjenane terhadap 12 negara Muslim menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara implementasi hisbah (institusi pengawasan moral-ekonomi) dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara, berbasiskan indikator yang menunjukkan bahwa legitimasi religius dapat memperkuat efektivitas govemance secara substansial. Ta’thir (dampak) transformatif dari pendekatan ini tidak terbatas pada dunia Arab semata, melainkan menawarkan model alternatif bagi negara-negara. berkembang yang menghadapi krisis legitimasi serupa pada proses pembangunannya. Prinsip adalah ijtima īyah dapat berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara aspirasi pembangunan
material dengan kebutuhan spiritual-moral masyarakat yang sering terabaikan di paradigma developmentalisme sekular dominan. Lebih fundamental lagi, pendekatan ini menantang hawlaqah (siklus) dependensi terhadap model pembangunan istishäri (konsultatif) yang dikembangkan di Barat tanpa mempertimbangkan konteks thaqafi (budaya) dan dini (religius) setempat sebagai variabel fundamental dalam proses pembangunan.
Dialektika antara aşālah dan tajdid (pembaruan) dalam konteks pembangunan dunia Arab meniscayakan terciptanya sintesis baru yang tidak sekadar mengadopsi atau menolak modemitas secara mekanistik, melainkan mentransformasinya sesuai dengan mabadi” (prinsip-prinsip) Islam melalui proses kreatif berkelanjutan. Di mana, proses transformatif ini memerlukan ijmä (konsensus) yang melibatkan ulama, intelektual, dan praktisi pembangunan untuk merumuskan kerangka teoritis dan praktis yang komprehensif, serta mampu menjembatani kesenjangan antara idealitas normatif dengan realitas empiris dalam konteks global kontemporer. Pertanyaan krusial yang tersisa dalam diskursus ini adalah apakah qiyädät (kepemimpinan) politik di dunia Arab memiliki irādah siyāsīyah (political will) yang memadai untuk mengimplementasikan transformasi paradigmatik ini secara konsisten, ataukah mereka akan terus terjebak dalam dawwamah (pusaran) dependensi terhadap model pembangunan yang terbukti gagal menciptakan keadilan sosial sebagai fondasi legitimasi politik jangka panjang. Jawaban atas pertanyaan fundamental ini, hemat kami tidak hanya menentukan trajectory masa depan dunia Arab, tetapi juga menentukan kontribusi substantif peradaban Islam terhadap pencarian alternatif global bagi krisis modemitas kapitalis yang semakin akut dalam era kontemporer. Wa Allahu alam bi al-sawab (dan Allah lebih mengetahui akan kebenaran).
*Tulisan ini dibuat oleh Dr. M. Agung Rahmadi, M.Si., Helsa Nasution, M.Pd., Luthfiah Mawar, M.K.M., dan Nurzahara Sihombing, S.Pd., Wildan Izzatulhaq, dan M. Ihsanul Yaziid (Corresponding Author: therolland15@gmail.com).
Bibliography:
Afzal Norat, M. (2015, April 15), Can Islamic finance support stability and inclusion? World Economic Forum. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2015/04/can-islamic-finance support-stability-and-inclusion/
ESCWA. (2023). Second Arab multidimensional poverty report. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. Retrieved from https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/second-arab-multidimensional-poverty-report-english.pdf
Montagu, C. (2015, March 31). Civil society in Saudi Arabia: The power and challenges of association. Chatham House. Retrieved from https://www.chathamhouse.org
Tao, Y., Wu, X., & Li, C. (2014). Rawls’ fairness, income distribution and alarming level of Gini coefficient, arXiv. Retrieved from https://arxiv.org/abs/1409.3979 UNDP. (2021). Islamic finance takes on COVID 19. UN Development Programme. Retrieved from
https://www.undp.org/blog/islamic-finance-takes-covid-19 World Bank. (2003). Better governance for development in the Middle East and North Africa:
Enhancing inclusiveness and accountability [PDF]. Retrieved from https://documents1.worldbank.org/curated/en/635011468330986995/pdf/394980REVISED0101 OFFICIALOUSEOONLY1 odf
World Bank. (2015, March 31). Islamic finance. The World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance
World Bank. (2024, October). Multidimensional poverty measure: Latest edition [Data]. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/multidimensional-poverty-measure
-10%